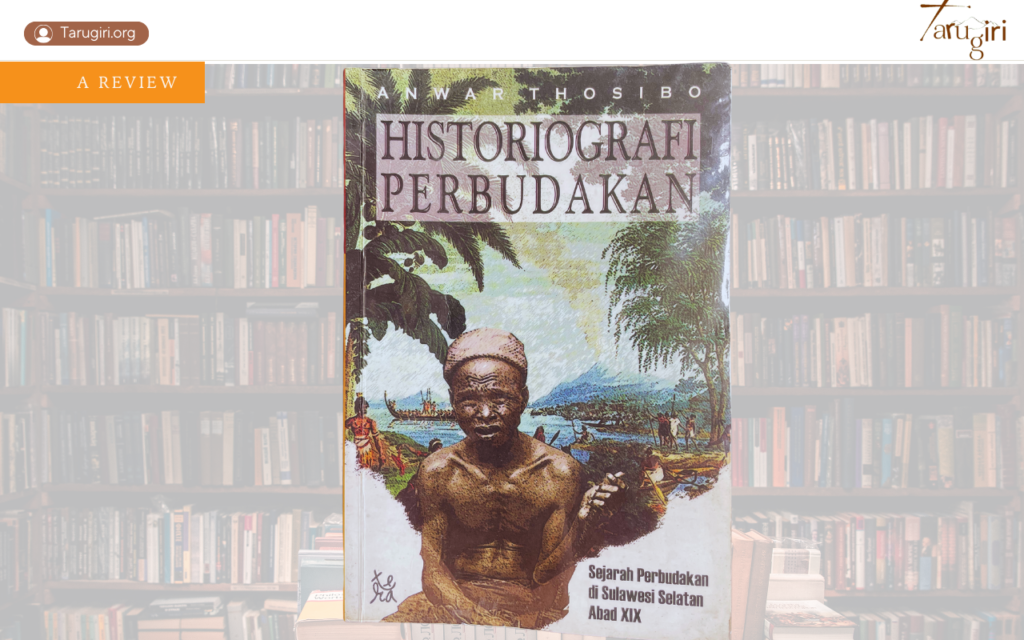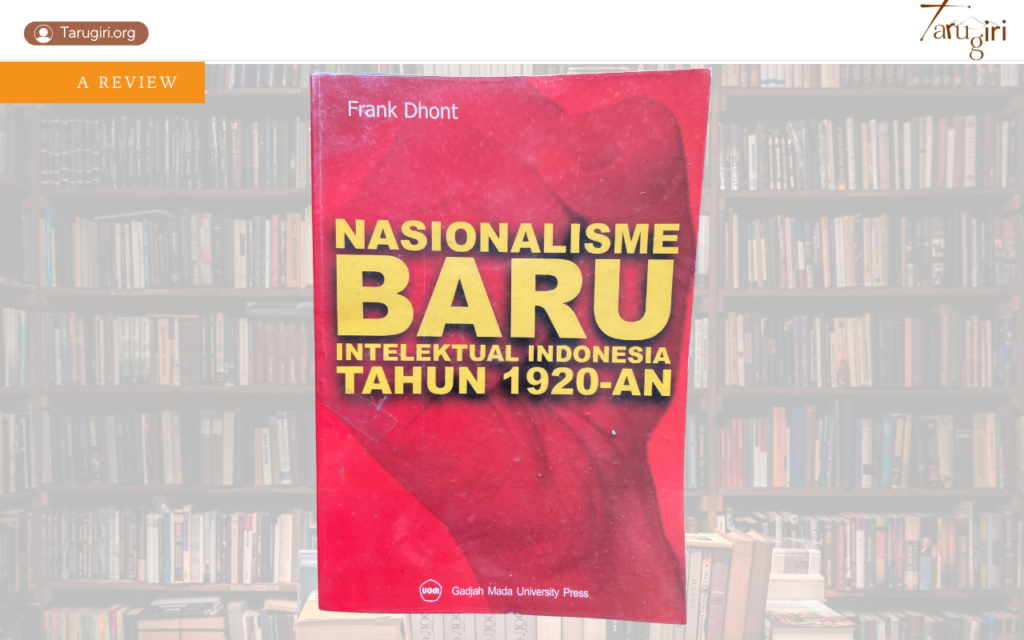| Judul | Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX/ Anwar Toshibo |
| Pengarang | Anwar Toshibo |
| Penerbitan | Magelang : Indonesiatera, 2002 |
| Deskripsi Fisik | VIII, 190 p. ;21 cm. |
| ISBN | 979-9375-41-X |
| Subjek | Sejarah – Sulawesi Selatan |
Pengantar Penerbit
Sampai dengan awal abad ke-20, tulisan mengenai kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Sulawesi Selatan telah banyak dihasilkan. Baik orang Portugis maupun pejabat pemerintah Hindia Belanda, para sarjana, dan kaum misionaris banyak memberikan sumbangan dalam mengisahkan “dunia” Bugis-Makassar di berbagai bidang.’ Tulisan-tulisan mereka telah menunjukkan suatu kedalaman pemahaman tentang berbagai permasalahan dan pandangan yang cukup jelas. Namun, perbedaan budaya mereka tidak memungkinkan untuk menerobos rintangan-rintangan kultural serta memahami cara berpikir masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.
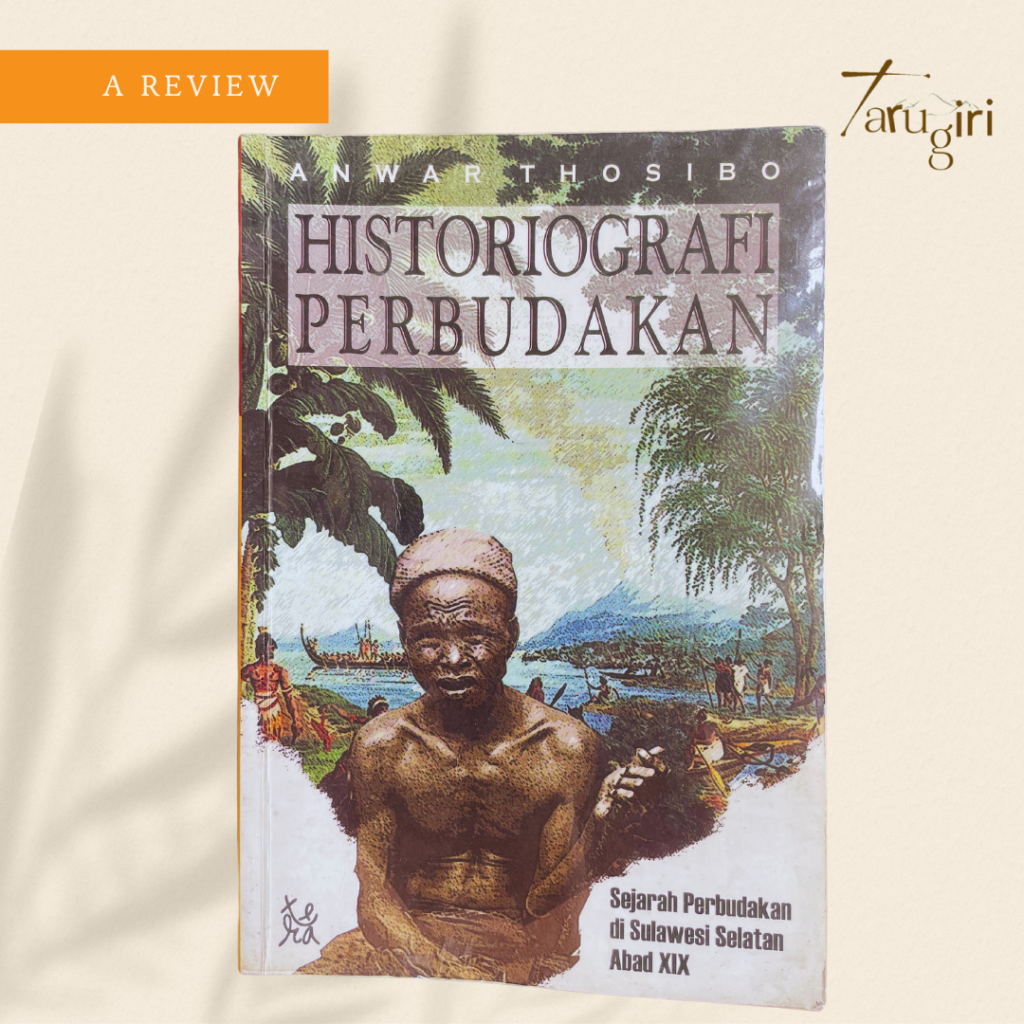
Adanya perbedaan dalam memahami suatu objek yang sama, oleh peneliti yang berbeda latar belakang kebudayaan, hanya bisa diterangkan jika memahami realitas yang ada di dalam diri orang-orang itu. Realitas ini terdiri dari gambaran-gambaran subjektif mengenai lingkungan mereka sebagaimana mereka memandangnya dengan kecenderungan kebudayaan yang mereka miliki. Inilah penyebab adanya tulisan-tulisan sejarah yang dihasilkan oleh peneliti asing – di antaranya membicarakan seiarah perbudakan-yang terbukti sangat bermanfaat untuk memahami masalah sejarah di samping masalah sosial lainnya, tetapi dianggap tidak realistis oleh orang Sulawesi Selatan sendiri.
Sehubungan dengan perbedaan pandangan tersebut, J.C. van Leur mengingatkan agar tidak hanya melihat sejarah Indonesia dari geladak kapal Belanda atau benteng VOC, seperti yang pernah dilakukan oleh banyak penulis Belanda. Dalam mempelajari sejarah Indonesia, termasuk sejarah Sulawesi Selatan, hendaknya dilakukan pendekatan dari “Indonesia”. Sartono Kartodirdjo mengistilahkan pendekatan in sebagai “penglihatan yang bersifat Indonesia-sentris”. Kemudian, pengertian ini dipertegas oleh Taufik Abdullah sebagai “etnis-kultural”. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan penulis untuk menyusun deskripsi sejarah perbudakan di Sulawesi Selatan, daerah tempat penulis dilahirkan dan dibesarkan, pada abad ke-19. Penulis pun berusaha melihat kenyataan itu dari dalam, bukan dari luar. Namun, dalam mendekati sejarah dari dalam, pendekatan melalui tembok istana atau bandar pelabuhan pun tidak boleh diabaikan.
Di samping itu, penulis asing juga sering kali menggunakan istilah atau kategori Eropa-Amerika untuk menganalisis realitas Indonesia tanpa mengetahui dengan tepat masalah yang sebenarnya. Padahal, suatu hal yang tidak mungkin bila kita dipaksakan menerima begitu saja penggunaan istilah secara umum dalam bahasa yang berbeda tapa suatu alasan yang mendasar. Mungkinkah kategori yang berasal dari sejarah Eropa, misalnya, cocok dengan tradisi sejarah Indonesia; apakah melalui cara penyamaannya, lantas diperoleh kekuatan penjelas yang lebih besar dengan menekankan hubungan suatu lembaga dengan lembaga lain yang sejenis pada masa dan tempat yang berlainan.
Setiap istilah mempunyai konotasi tersendiri, yang oleh orang asing cenderung dibawa saat membicarakan situasi Sulawesi Selatan. Dipandang dari segi politik dan ekonomi, “slavery ” mempunyai konotasi eksploitasi tenaga manusia. Karena itu, terjadilah suatu penilaian moral yang negatif terhadap gejala yang dilihat sebagai perbudakan oleh dunia Barat di Sulawesi Selatan. Meskipun ada unsur perhambaan dan ketergantungan, terlalu cepat dinilai negatif bila kegiatan tersebut dicap sebagai “perbudakan”. Mungkin benar bila dalam istilah umum bahasa Eropa satu-satunya istilah yang sama-sama memiliki beban emosi merendahkan adalah “rasisme’ , sementara apa yang sekarang kita sebut “rasisme” bisa dipandang sebagai kategori orang luar yang menghamba.
Oleh karena itu, perbudakan yang mempunyai konotasi merendahkan merupakan contoh yang sangat menarik untuk dibicarakan. Lebih penting lagi untuk dapat mengetahui bahwa institusi perbudakan telah mencakup berbagai macam masyarakat yang terdapat di berbagai tempat di dunia pada masa yang lalu. Tidak hanya terbatas pada lingkungan masyarakat Afrika dan Eropa, tetapi juga terjadi di Asia Tenggara. Bahkan, keabsahan kegiatan perdagangan budak pernah menjadi persoalan internasional.’ Menurut kamus Inggris-Indonesia, kata slavery berarti ‘”perbudakan’ atau ‘bekerja keras”: sementara di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “budak” berarti “hamba” atau “anak-anak”. Dengan kata lain, istilah “slavery“, yang dalam hal in mempunyai kesan penindasan, sama pengertiannya dengan perhambaan, ketergantungan, serta hubungan dyadik yang lebih manusiawi. Pengertian ini menunjukkan terjadinya, antitesis antara suatu kategori dengan kategori lain yang begitu luas pengertiannya sehingga hampir menjadi tidak berarti. Mattulada, sepanjang uraiannya mengenai budaya dan politik orang Bugis-Makassar masa lalu dengan tegas menolak penggunaan istilah perbudakan dan kegiatan yang berhubungan dengan kata itu. Miers dan Kopytoff pun menganjurkan kita untuk membuang konsep-konsep Barat ketika kita berusaha memahami apa yang oleh pengamat Barat, karena berbagai alasan, disebut dengan perbudakan di Afrika. Posisi perbudakan seharusnya diuji dalam konteks masyarakat setempat sehingga dapat dipahami arti setiap lembaga bagi orang yang ada di dalam sistem itu. Namun kenyataannya, setelah menulis sistem itu di Sulawesi Selatan, mereka segera memulai proses penyamaan dengan sejumlah kategori di luar.
Selain itu, penulis juga berpandangan bahwa perbudakan merupakan salah satu istilah yang cukup penting dalam analisis sosial budaya dan sejarah komparatif. Pada saat mendefinisikan istilah ini dengan jelas dan menguji kebudayaan serta sistem sosial yang menggunakan istilah ini di dalamnya, akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang seberapa jauh pengalaman budak Bugis-Makassar merupakan suatu perkembangan, suatu variasi atau suatu pengecualian dari pola-pola yang lebih umum. Lebih dari itu, ditemukan bahwa kategori budak menjadi paling penting, paling jelas, persis pada pertemuan dua budaya ketika tenaga kerja ditransfer dari masyarakat yang relatif kuat dan kaya. Untuk memahami sifat pertukaran ini dan apa artinya bagi kedua belah pihak. perlu dicari definisi yang berguna dan cocok untuk pembeli maupun penjual, tuan maupun hamba, tradisional maupun modern.
Dari sekian banyak definisi yang diberikan oleh para ahli, definisi yang paling bermanfaat dan diharapkan cocok untuk situasi daerah Sulawesi Selatan adalah definisi yang diberikan oleh Nie Boer, ‘ Kita bisa mendefinisikan seorang budak pada umumnya sebagai (1) seorang yang merupakan hak milik orang lain; (2) baik secara politik maupun sosial berada dalam tingkat yang lebih rendah dibanding dengan kebanyakan orang; dan (3) orang yang melakukan pekerjaan wajib.” Demikian pula Watson, secara tepat budak didefinisikannya sebagai orang hak milik dan pekerja wajib.” Kedua definisi tersebut tidak akan dipersoalkan lagi benar tidaknya, tetapi diuji pada bentuk-bentuk perbudakan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi dari sumber-sumber setempat, dapat diketahui bahwa ada sejumlah suku bangsa di Sulawesi Selatan yang sejak jauh masa silam telah mengenal lembaga perbudakan, bahkan sudah melekat dalam struktur kemasyarakatannya.
INDONESIATERA